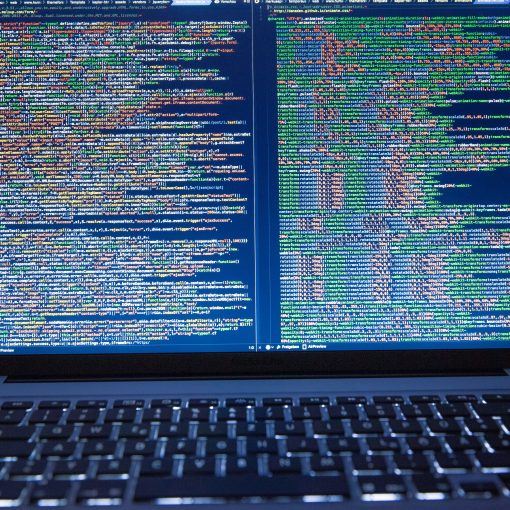ilustrasi : Freepik.com
ilustrasi : Freepik.com
Oleh : Jean Alvita Belinda Putri
Globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang teknologi. Kemajuan pesat teknologi semakin mempermudah segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sosial media menjadi salah satu contoh nyata dari perkembangan teknologi yang membantu manusia untuk saling berinteraksi. Selain untuk meningkatkan komunikasi, sosial media juga menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai media untuk menyuarakan demokrasi. Seiring dengan perkembangannya, sosial media tidak selalu membawa dampak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Kini, sosial media sering menjadi wadah untuk saling menghina, menyebarkan ujaran kebencian, memberitakan berita bohong (hoax), melakukan penipuan dan lain sebagainya. Supaya terhindarkan dari terjadinya dampak buruk yang dapat merugikan publik serta menyeimbangkan kepentingan manusia dalam dunia maya tersebut, pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup etika dan pembatasan untuk berinteraksi di dunia maya salah satu nya ialah dengan adanya UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Cancel culture adalah sebuah budaya dimana publik melalui media sosial melakukan pemboikotan kepada individu tertentu yang memiliki tingkat popularitas karena hal-hal tertentu yang dinilai buruk oleh masyarakat seperti rasisme dan etnis; pelecehan seksual; dan ujaran kebencian terhadap wanita, identitas gender non-biner, transphobia.[1] Publik menganggap bahwa cancel culture ditujukan untuk memperkuat atau memberlakukan norma-norma yang menetapkan cara bertindak dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat[2] seperti yang terjadi dalam fenomena cancel culture pada aksi “Black Lives Matter” atau “Stop Asian Hate”. Dikutip dari artikel yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School mengatakan bahwa strategi cancel culture ini pada umumnya menggunakan sosial media untuk mempermalukan seseorang dengan maksud memberikan hukuman dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari membatasi akses ke platform publik, merusak reputasi seseorang, dan mengakhiri karir seseorang hingga menghasut untuk melakukan penuntutan secara hukum.[3]
Contoh faktual dari aksi cancel culture ini pernah dialami oleh salah seorang Youtuber ternama James Charles. James Charles merupakan seorang beauty Youtuber yang memiliki lebih dari 25.5 juta subscribers diboikot massa pada April 2021 karena tindakannya mengirimkan pesan yang mengandung unsur seksual kepada dua anak laki-laki dibawah umur.[4] Hal tersebut memunculkan berbagai kemarahan dan kritik dari para penggemar James Charles. Akibat dari aksi cancel culture tersebut, Morphe selaku perusahaan tata rias yang mempekerjakan James sejak 2016 memutuskan hubungan kerja dengan sang YouTuber usai mencuatnya boikot massal yang dialami oleh James.[5] Di Indonesia sendiri kasus cancel culture juga pernah menimpa salah satu perusahaan start-up terbesar yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih kerap disebut Gojek Indonesia. Pada tahun 2018, tagar #UninstallGojek sempat menjadi tranding dalam platform Twitter usai seorang Vice President Operations and Business Development dari Gojek Indonesia mengunggah postingan mengenai dukungannya terhadap komunitas LGBT.[6]
Pada umumnya, bentuk daripada cancel culture serupa dengan tindakan ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.[7] Akan tetapi, hingga saat ini sistem hukum yang ada di Indonesia masih mencampuradukan konsep cancel culture dengan konsep ujaran kebencian (hate speech) ke dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.[8] Suatu fenomena cancel culture akan berubah menjadi sebuah ujaran kebencian (hate speech) apabila unsur delik dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terpenuhi. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani suatu perkara ujaran kebencian (hate speech) berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (hate speech). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri tersebut, disebutkan beberapa bentuk ujaran kebencian (hate speech) diantaranya: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penistaan, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran Berita Bohong, dan segala tindakan yang mempunyai tujuan atau dapat berdampak terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.[9]
Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE termasuk ke dalam unsur delik aduan. Delik aduan dapat diartikan bahwa untuk dapat melakukan proses hukum dibutuhkan adanya pengaduan.[10] Setidaknya terdapat 3 (tiga) kejahatan yang termasuk kedalam kualifikasi delik aduan dalam KUHP yaitu bab XVI KUHP tentang penghinaan; kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengandaman serta penggelapan; dan kejahatan terhadap kesusilaan.[11] Sebuah fenomena cancel culture dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik apabila telah memenuhi unsur delik yang di persangkakan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut :
- Setiap orang: individu yang menjadi penyebar/sumber dapat menjadi tersangka/terdakwa apabila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Dengan Sengaja dan tanpa hak: unsur ini harus dibuktikan dengan kepada siapa saja penyebar memberitahukan informasi/dokumen elektronik dan atas dasar tujuan apa yang dituju;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: unsur ini terpenuhi apabila informasi/dokumen elektronik tersebut dapat diakses secara umum oleh berbagai pihak;
- Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: unsur ini pada dasarnya harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut oleh bantuan ahli bahasa dalam pembuktiannya. [12]
Pada dasarnya, fenomena cancel culture merupakan cikal bakal dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Main hakim sendiri adalah tindakan pelaksanaan hak berdasarkan kehendak diri sendiri secara sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkaitan.[13] Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, cancel culture dapat menjadi bentuk kontrol dari norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Tidak hanya norma hukum yang bekerja, fenomena cancel culture dapat dinilai sebagai bentuk implementasi dari norma kesusilaan dan norma kesopanan yang juga berfungsi sebagai penentu perubahan sikap serta perilaku seseorang dengan mengedepankan moralitas.[14] Akan tetapi, perlu adanya limitasi terhadap perilaku cancel culture tersebut. Bentuk limitasi seperti minimal umur untuk dapat mendaftar akun sosial media, pembatasan terhadap konten-konten yang diunggah ke sosial media, pengisian data diri dan proteksi akun.
[1] Pippa Norris, “Closed Minds? Is a ‘Cancel Culture’ Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science”, Faculty Research Working Paper Series, (August 2020) : 2.
[2] Loydie Solange Burmah, “The Curious Cases of Cancel Culture”, (Electronic Theses, Projects, and Dissertations., California State University, 2021) :11
[3] Ibid.
[4] Cody Godwin, “James Charles : YouTube Star Admits Messaging 16-year-old Boys”, BBC News https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56611614 (diakses 9 Juli 2021).
[5] Taylor Lorenz dan Valeriya Safronova, “Why James Charles Has Been Demonetized by YouTube”, The New York Times https://www.nytimes.com/2021/04/21/style/james-charles-youtube-demonetized.html (diakses 9 Juli 2021).
[6] Karina M. Tehusijarana, “#UninstallGojek Trends After Executive Show Support for LGBT Community”, The Jakarta Post https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/14/uninstallgojek-trends-after-executive-shows-support-for-lgbt-community.html (diakses 24 Agustus 2021).
[7] Sudut Hukum, “Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, Sudut Hukum http://www.suduthukum.com, (diakses 24 April 2021).
[8] Benedictus Avianto Pramana, “Hate Speech dan Cancel Culture di Indonesia, Apakah sama?”, Legistra https://legistra.id/berita/hate-speech-dan-cancel-culture-di-indonesia-apakah-sama (diakses 14 Agustus 2021).
[9] Hukum Online, “Keberlakuan SE Kapolri Hate Speech dan Dampak Hukumnya”, Hukum Online https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt563accb796101/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya (diakses 14 Agustus 2021).
[10] Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 145.
[11] Ibid. 145-147.
[12] Rizky P.P Karo Karo, “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pencemaran Nama Baik”, Hukumonline.com https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d83b35260ae6/perlindungan-hukum-bagi-tersangka-pencemaran-nama-baik/ (diakses pada 10 Juli 2021).
[13] Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”, (Yogyakarta: Liberty, 2007) : 23.
[14] Loydie Solange Burmah., Op.cit : 10.